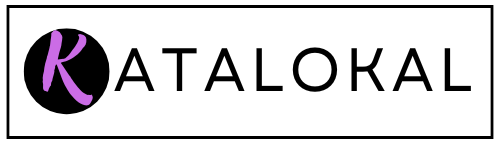Real Madrid selalu hidup dari bintang. Sejarah klub ini ditulis oleh nama-nama besar, dari Di Stéfano hingga Cristiano Ronaldo. Namun di balik kilau galácticos, ada satu paradoks lama yang terus berulang: ketika terlalu banyak bintang berada di satu panggung, ego kerap lebih terang daripada sistem. Dalam konteks inilah isu star syndrome kembali mengemuka, terutama setelah keputusan mengejutkan Xabi Alonso untuk mundur dari jabatannya.
Xabi Alonso dikenal bukan sekadar legenda Madrid, tetapi juga pelatih dengan pendekatan taktik yang rapi, modern, dan berbasis kolektivitas. Ia datang dengan visi: membangun tim yang bekerja sebagai sistem, bukan sekadar panggung unjuk individu. Namun visi itu tampaknya berbenturan dengan realitas ruang ganti Real Madrid—ruang yang diisi pemain-pemain berstatus superstar, dengan pengaruh besar di media, publik, dan bahkan manajemen.
Star syndrome bukan soal kualitas pemain, melainkan soal hierarki tak tertulis. Di klub seperti Madrid, ada pemain yang secara simbolik “tak tersentuh”. Mereka bukan hanya atlet, tetapi juga aset komersial, ikon global, dan wajah klub. Dalam situasi seperti ini, keputusan taktik pelatih sering kali harus bernegosiasi dengan ego, reputasi, dan ekspektasi personal.
Ketika seorang pelatih menuntut disiplin posisi, kerja defensif kolektif, atau rotasi pemain, benturan menjadi tak terelakkan. Beberapa pemain merasa perannya diperkecil, menit bermainnya terancam, atau kebebasan berekspresinya dibatasi. Di sinilah konflik sunyi muncul—bukan dalam bentuk pemberontakan terbuka, melainkan atmosfer ruang ganti yang tidak lagi sinkron.
Mundurnya Xabi Alonso dapat dibaca sebagai simbol kelelahan struktural. Bukan karena ia gagal secara teknis, tetapi karena sistem yang ingin ia bangun tidak sepenuhnya mendapat ruang untuk tumbuh. Di Real Madrid, pelatih sering kali dituntut untuk menyesuaikan diri dengan bintang, bukan sebaliknya. Dan bagi pelatih dengan idealisme taktik yang kuat, kompromi semacam itu bisa menjadi titik jenuh.
Ironisnya, Real Madrid tetap bisa menang dalam situasi seperti ini. Kualitas individu sering kali menyelamatkan hasil akhir. Namun kemenangan semacam itu tidak selalu mencerminkan kesehatan jangka panjang tim. Ia menunda masalah, bukan menyelesaikannya.
Kasus Xabi Alonso menunjukkan bahwa tantangan terbesar di Real Madrid bukan mencari pelatih hebat atau pemain berbakat—keduanya selalu tersedia. Tantangannya adalah menundukkan ego kolektif demi visi bersama. Selama star syndrome masih menjadi budaya yang tak tersentuh, maka siapa pun pelatihnya akan berada di posisi rawan: antara menjaga sistem atau mengalah pada bintang.
Dan ketika seorang pelatih memilih mundur, itu bukan semata tanda kegagalan pribadi. Bisa jadi, itu adalah cara paling elegan untuk mengatakan bahwa sepak bola seharusnya dimenangkan oleh tim, bukan oleh nama.