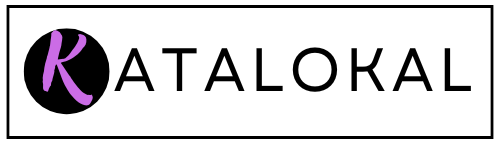Probolinggo – Dalam setiap pemerintahan dan organisasi, kegiatan seremonial hampir selalu hadir. Pelantikan, peresmian, penandatanganan kerja sama, hingga rapat-rapat formal yang dibalut protokol rapi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan birokrasi. Di satu sisi, seremoni sering dipandang sebagai kebutuhan institusional. Namun di sisi lain, tak sedikit yang menganggapnya sebagai pemborosan waktu dan anggaran. Pertanyaannya kemudian: apakah kegiatan seremonial benar-benar penting?
Secara fungsi, kegiatan seremonial memiliki peran simbolik yang kuat. Ia menjadi penanda resmi bahwa sebuah kebijakan, program, atau lembaga diakui dan dimulai. Dalam konteks pemerintahan, seremoni sering kali menjadi wajah kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia mengirim pesan bahwa negara hadir, bekerja, dan bertanggung jawab. Simbol semacam ini penting, terutama di masyarakat yang masih memaknai legitimasi melalui tanda-tanda formal.
Di dalam organisasi, kegiatan seremonial juga berfungsi membangun identitas dan kebersamaan. Pelantikan pengurus, rapat kerja, atau deklarasi program bukan hanya soal prosedur, tetapi juga momentum psikologis. Seremoni menciptakan rasa memiliki, memperkuat komitmen, dan menandai peralihan dari niat ke tindakan. Banyak orang terdorong bergerak bukan semata oleh aturan tertulis, tetapi oleh momen yang dirayakan bersama.
Namun, persoalan muncul ketika kegiatan seremonial menjadi tujuan itu sendiri. Ketika kesuksesan diukur dari ramainya acara, banyaknya dokumentasi, dan luasnya publikasi, sementara substansi kerja justru tertinggal. Dalam kondisi seperti ini, seremoni kehilangan makna dan berubah menjadi ritual kosong. Ia tampak megah di permukaan, tetapi miskin dampak bagi masyarakat atau anggota organisasi.
Lebih problematis lagi, jika seremoni dijadikan alat pencitraan semata. Alih-alih menjadi sarana akuntabilitas, ia justru menutupi kinerja yang lemah. Program diluncurkan berkali-kali, kerja sama diresmikan berulang, tetapi hasil nyata sulit dirasakan. Publik disuguhi kesan seolah-olah ada banyak gerak, padahal perubahan substantif berjalan lambat.
Idealnya, kegiatan seremonial ditempatkan secara proporsional. Ia penting sebagai penanda awal, bukan puncak dari sebuah kerja. Seremoni seharusnya menjadi pintu masuk menuju proses yang lebih panjang: perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang terbuka. Tanpa tindak lanjut yang konkret, seremoni hanya akan menjadi arsip foto dan berita sesaat.
Pada akhirnya, kegiatan seremonial bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi perlu dimaknai ulang. Ia bernilai ketika selaras dengan kerja nyata, dan menjadi tidak relevan ketika menggantikan kerja itu sendiri. Pemerintahan dan organisasi yang sehat bukan yang paling sering menggelar seremoni, melainkan yang mampu menjadikan setiap seremoni sebagai komitmen awal untuk bekerja lebih serius, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab.