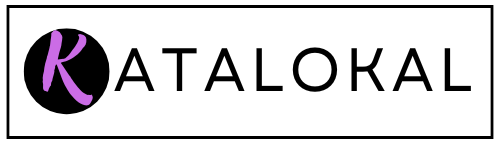Jakarta – 02 Februari 2026, Keputusan pemerintah mendatangkan lebih dari seribu sapi perah dari Australia untuk memperkuat industri susu nasional tampak sebagai langkah besar yang ambisius. Di atas kertas, kebijakan ini terlihat logis: produksi susu dalam negeri masih rendah, ketergantungan impor tinggi, sementara kebutuhan gizi masyarakat terus meningkat. Namun jika dibaca lebih dalam, langkah ini menyisakan pertanyaan mendasar: apakah impor sapi perah benar-benar solusi jangka panjang, atau sekadar jalan pintas yang menunda pekerjaan rumah yang lebih besar?
Impor sapi perah sering dibingkai sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Tetapi ketahanan pangan sejatinya bukan sekadar soal menambah populasi ternak, melainkan tentang membangun ekosistem produksi yang kuat dan mandiri. Tanpa ketersediaan pakan lokal yang berkelanjutan, sistem kesehatan hewan yang memadai, teknologi pengolahan susu yang merata, serta pasar yang adil bagi peternak kecil, sapi-sapi impor itu berisiko menjadi simbol kebijakan yang besar secara angka namun rapuh secara struktur.
Kebijakan ini juga memperlihatkan kecenderungan lama negara berkembang: ketika produksi domestik tertinggal, solusi tercepat adalah membeli dari luar. Padahal, dengan pendekatan seperti ini, ketergantungan tidak benar-benar diputus, hanya dipindahkan bentuknya. Dari impor susu menjadi impor sapi, dari produk jadi ke bahan baku. Negara tetap berada dalam posisi bergantung, hanya dengan narasi yang lebih optimistis.
Yang lebih krusial adalah posisi peternak kecil. Pemerintah menyebut pelibatan peternak rakyat sebagai bagian dari program, namun pengalaman kebijakan serupa menunjukkan bahwa tanpa pendampingan serius, akses pembiayaan, dan perlindungan harga, peternak kecil sering kali hanya menjadi pelengkap. Jika industri pengolahan dan distribusi tetap dikuasai pemain besar, maka risiko ditanggung peternak, sementara keuntungan terkonsentrasi di hilir.
Masalah industri susu nasional sejatinya bukan kekurangan sapi semata, melainkan lemahnya fondasi riset, pakan ternak, dan tata niaga. Selama persoalan-persoalan ini tidak dibenahi, impor sapi perah berpotensi menjadi kebijakan yang tampak progresif, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Ia memberi kesan bergerak cepat, namun justru menjauh dari upaya membangun kemandirian.
Pada akhirnya, langkah ini bisa disebut bijak jika diposisikan sebagai solusi sementara, bukan sebagai tumpuan utama. Namun jika impor sapi perah dijadikan jalan utama tanpa diiringi pembangunan ekosistem peternakan yang kuat, kebijakan ini berisiko menjadi pengulangan pola lama: ambisi besar, hasil terbatas, dan ketergantungan yang terus diwariskan. Dalam konteks ketahanan pangan, yang dibutuhkan bukan sekadar langkah cepat, melainkan keberanian untuk membangun dari hulu, meski jalannya lebih panjang dan menuntut konsistensi.