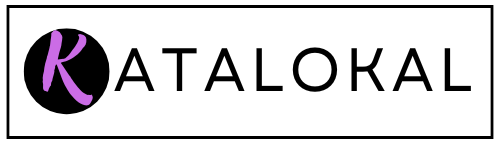Ibadah haji adalah puncak spiritualitas umat Islam. Namun, ketika pengelolaannya terseret isu korupsi, yang tercoreng bukan hanya sistem birokrasi, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara dan otoritas moral pejabatnya.
Belakangan ini, publik dikejutkan oleh mencuatnya dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menyeret nama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Meski proses hukum masih berjalan dan asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi, kasus ini membuka ruang refleksi yang lebih luas: apakah tata kelola haji di Indonesia sudah benar-benar bersih dari konflik kepentingan dan politisasi kekuasaan?
Haji: Antara Ibadah, Bisnis, dan Kekuasaan
Setiap tahun, penyelenggaraan haji melibatkan anggaran besar, kewenangan administratif luas, serta relasi internasional yang kompleks. Dalam konteks ini, Kementerian Agama memegang posisi strategis—sekaligus rentan.
Ketika muncul dugaan pengaturan kuota, akomodasi, atau layanan yang tidak transparan, persoalannya bukan semata soal pelanggaran hukum, tetapi kegagalan etika tata kelola publik. Haji seharusnya dikelola dengan prinsip amanah, keadilan, dan pelayanan, bukan dengan logika transaksional yang membuka celah penyimpangan.
Nama Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan bukan hanya karena jabatan yang diembannya, tetapi juga karena simbol yang melekat: seorang tokoh agama yang memimpin institusi keagamaan negara. Di titik inilah krisis menjadi berlapis—krisis hukum, krisis birokrasi, dan krisis moral.
Ketika Legitimasi Moral Dipertaruhkan
Dalam sistem demokrasi, pejabat publik tidak hanya dinilai dari sah atau tidaknya tindakan secara hukum, tetapi juga dari kelayakan moral dan etika publik. Dugaan korupsi dalam urusan haji, jika benar terbukti, akan menjadi preseden buruk: negara gagal melindungi ibadah umat dari kepentingan duniawi.
Lebih dari itu, kasus ini memperlihatkan problem klasik birokrasi Indonesia: sentralisasi kewenangan tanpa pengawasan yang memadai. Selama pengelolaan haji masih dikuasai oleh satu otoritas besar dengan kontrol terbatas, potensi penyimpangan akan selalu ada—siapa pun menterinya.
Publik Berhak Bertanya, Negara Wajib Menjawab
Opini publik yang kritis bukanlah bentuk penghakiman, melainkan mekanisme kontrol demokrasi. Masyarakat berhak mempertanyakan:
-
Apakah pengelolaan haji sudah transparan?
-
Di mana peran audit independen?
-
Mengapa masalah serupa terus berulang dari tahun ke tahun?
Kasus yang menyeret nama Yaqut Cholil Qoumas seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar persoalan individu. Negara tidak cukup hanya menyerahkan semuanya pada proses hukum, tetapi juga perlu membangun ulang sistem yang akuntabel, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan jamaah.
Penutup: Haji Tidak Boleh Dikorbankan
Jika haji—ibadah yang paling sakral dan mahal secara spiritual—masih bisa dijadikan ladang kepentingan, maka ada yang keliru dalam cara negara memaknai amanah. Korupsi dalam urusan haji bukan sekadar kejahatan administratif; ia adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan umat.
Siapa pun yang terlibat, hukum harus berjalan. Namun yang lebih penting, sistem harus diperbaiki, agar haji kembali menjadi urusan ibadah, bukan arena kekuasaan.
⚠️ DISCLAIMER OPINI
Tulisan ini merupakan opini penulis berdasarkan analisis dan perspektif pribadi terhadap isu publik yang berkembang. Artikel ini tidak bermaksud menuduh, menghakimi, atau menyatakan kesalahan hukum pihak mana pun. Seluruh pihak yang disebutkan tetap dilindungi oleh asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Tulisan ini disusun untuk tujuan refleksi, diskursus publik, dan pendidikan demokrasi.