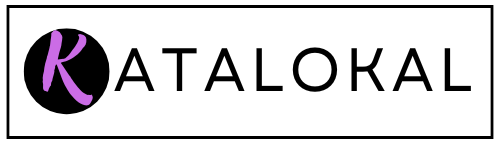Ungkapan “2026 is the new 2016” yang ramai di media sosial bukan sekadar permainan kata atau tren nostalgia musiman. Ia adalah penanda kegelisahan kolektif. Tahun 2016 diingat sebagai masa yang terasa lebih sederhana: media sosial belum seintens sekarang, algoritma belum terlalu agresif, dunia belum sepenuhnya dikepung kecemasan global, dan hidup—setidaknya dalam ingatan—terasa lebih ringan.
Nostalgia ini muncul di tengah dunia yang bergerak terlalu cepat. AI, krisis iklim, konflik geopolitik, tekanan ekonomi, dan budaya kerja serba instan membuat banyak orang merasa kehilangan pijakan emosional. Maka, 2016 menjadi semacam “ruang aman imajiner”—bukan karena semuanya benar-benar lebih baik, tetapi karena jaraknya cukup jauh untuk dimaknai ulang tanpa beban realitas hari ini.
Menariknya, nostalgia ini tidak hanya soal musik, fesyen, atau estetika media sosial. Ia adalah kritik halus terhadap zaman kini. Ketika orang merindukan era timeline yang tidak terlalu penuh iklan, pertemanan yang terasa lebih organik, dan hidup yang tidak selalu dituntut produktif, sesungguhnya mereka sedang mempertanyakan arah peradaban digital saat ini. Nostalgia menjadi bahasa protes yang paling lembut.
Namun, di sisi lain, nostalgia juga bisa menipu. Ia berisiko membuat kita terjebak romantisasi masa lalu, seolah-olah kembali ke 2016 adalah solusi. Padahal, setiap zaman punya problemnya sendiri. Yang lebih penting bukan kembali ke tahun tertentu, melainkan mengambil nilai-nilai yang hilang: jeda, kesederhanaan, relasi yang lebih manusiawi, dan kendali atas teknologi—bukan sebaliknya.
Pada akhirnya, “2026 is the new 2016” bukan ajakan mundur, melainkan refleksi. Ia mengingatkan bahwa kemajuan tanpa makna hanya akan melahirkan kelelahan kolektif. Jika 2016 dirindukan karena manusia masih merasa menjadi pusat hidupnya sendiri, maka tugas kita di 2026 adalah merebut kembali peran itu—di tengah dunia yang semakin bising dan serba otomatis.