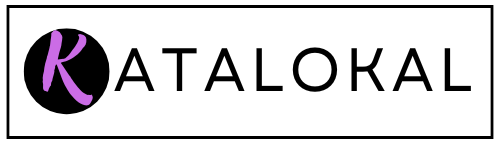Kasus operasi tangkap tangan yang menjerat kepala daerah selalu menghadirkan ironi yang pahit. Di satu sisi, mereka adalah figur yang dipilih melalui proses demokrasi, dipercaya memimpin daerah, menjaga anggaran publik, dan menjadi wajah negara di hadapan masyarakat. Namun di sisi lain, ketika justru mereka yang tertangkap dalam pusaran praktik pemerasan dan suap, kepercayaan itu runtuh seketika.
Peristiwa yang menimpa Bupati Pati dan Wali Kota Madiun memperlihatkan betapa rapuhnya integritas kekuasaan ketika kewenangan tidak dibarengi kontrol moral yang kuat. Dalam kasus Bupati Pati, publik disuguhi narasi pembelaan diri dengan klaim “dikorbankan”. Narasi semacam ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah penegakan hukum korupsi di Indonesia. Hampir selalu, pejabat yang terseret OTT berusaha membingkai dirinya sebagai korban sistem, tekanan politik, atau konflik internal. Namun klaim tersebut menjadi problematis ketika berhadapan dengan fakta-fakta hukum berupa alur uang, kesaksian, dan barang bukti yang menunjukkan adanya pola penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bersifat insidental.
Sementara itu, kasus Wali Kota Madiun menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung hukum di tengah citra kepemimpinan yang sebelumnya dikenal publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa citra populis, kedekatan dengan rakyat, atau keberhasilan pembangunan fisik tidak otomatis sejalan dengan praktik tata kelola yang bersih. Justru di tingkat lokal, relasi kekuasaan sering kali lebih personal, tertutup, dan minim pengawasan, sehingga membuka ruang transaksi gelap yang sulit terdeteksi tanpa operasi penindakan langsung.
Ironi terbesar dari kasus-kasus ini adalah kontradiksi antara mandat dan praktik. Kepala daerah memiliki kekuasaan besar dalam pengambilan keputusan, mulai dari pengisian jabatan, perizinan, hingga distribusi sumber daya. Ketika kewenangan tersebut digunakan sebagai alat pemerasan atau komoditas transaksi, maka negara hadir bukan sebagai pelayan publik, melainkan sebagai alat rente. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan sosial, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses atau daya tawar dalam sistem kekuasaan.
Kasus OTT kepala daerah seharusnya tidak dipahami semata sebagai kegagalan individu, tetapi juga sebagai sinyal adanya masalah struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah. Lemahnya sistem pengawasan internal, budaya birokrasi yang permisif terhadap praktik transaksional, serta minimnya keteladanan etis di pucuk pimpinan menjadi kombinasi yang berbahaya. Selama jabatan masih dipersepsikan sebagai sumber kekuasaan ekonomi, bukan amanah pelayanan, maka potensi korupsi akan selalu ada, siapa pun orangnya.
Pada akhirnya, ironi ini menjadi pengingat bahwa demokrasi elektoral tidak otomatis melahirkan pemerintahan yang bersih. Pemilihan langsung hanyalah pintu masuk kekuasaan, bukan jaminan integritas. Tanpa penguatan sistem pencegahan, transparansi, dan budaya akuntabilitas yang konsisten, OTT akan terus berulang, dan publik akan terus menyaksikan siklus yang sama: pemimpin dielu-elukan di awal, lalu jatuh dalam skandal yang mencederai kepercayaan masyarakat.