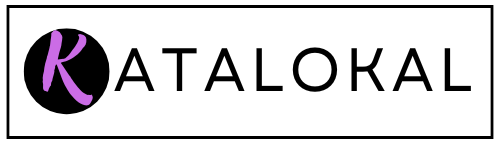Jakarta – Keputusan pemerintah mengangkat sekitar 32.000 PPPK untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menandai keseriusan negara dalam menjawab persoalan gizi dan kualitas sumber daya manusia. Namun, di saat yang sama, kebijakan ini memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dihindari: mengapa negara begitu cepat menghadirkan kepastian bagi program baru, sementara guru dan tenaga kesehatan honorer yang telah puluhan tahun mengabdi masih terus menunggu kejelasan nasib?
Secara moral dan kebijakan publik, pertanyaan ini sah untuk diajukan.
Guru dan tenaga kesehatan honorer bukanlah aktor baru dalam sistem pelayanan publik. Mereka telah menjadi tulang punggung pendidikan dan kesehatan, bahkan jauh sebelum istilah reformasi birokrasi populer. Di daerah terpencil, sekolah dan puskesmas kerap tetap berjalan bukan karena kelengkapan fasilitas, melainkan karena dedikasi honorer yang bertahan dengan insentif minim dan status kerja yang rapuh.
Ironisnya, ketika negara dengan cepat menyiapkan skema PPPK untuk program MBG—yang sejatinya bersifat programatik dan temporer—guru dan nakes honorer yang menjalankan fungsi inti negara justru terjebak dalam ketidakpastian bertahun-tahun. Banyak dari mereka berulang kali mengikuti seleksi, terhambat usia, atau kalah oleh sistem afirmasi yang berubah-ubah.
Dari perspektif kebijakan, pemerintah memang dapat berargumen bahwa MBG membutuhkan sumber daya manusia baru agar program berjalan efektif. Namun, argumen ini menjadi problematis ketika negara terlihat lebih responsif terhadap kebutuhan program baru ketimbang memperbaiki ketimpangan struktural lama. Seolah-olah, loyalitas dan pengabdian panjang tidak cukup kuat menjadi dasar pengakuan.
Lebih jauh, terdapat persoalan keadilan anggaran. Pengangkatan puluhan ribu PPPK baru tentu menyerap belanja pegawai dalam jumlah besar. Di sisi lain, guru dan nakes honorer masih banyak yang digaji di bawah standar hidup layak, bahkan bergantung pada dana BOS atau iuran daerah. Jika negara mampu menanggung beban fiskal untuk MBG, mengapa keberanian yang sama tidak hadir untuk menyelesaikan persoalan honorer secara menyeluruh?
Kebijakan publik seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia dilaksanakan, tetapi juga seberapa adil ia memprioritaskan. Tanpa keberanian menata ulang skala prioritas, kebijakan berisiko menciptakan kecemburuan sosial di internal pelayanan publik sendiri. Program MBG yang diniatkan mulia justru bisa dipersepsikan sebagai simbol ketimpangan kebijakan.
Bukan berarti pengangkatan PPPK MBG harus ditolak. Program gizi tetap penting. Namun, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi etis: bahwa membangun generasi sehat tidak bisa dilepaskan dari guru yang mendidik dan nakes yang menjaga kesehatan mereka. Menguatkan MBG tanpa menyelesaikan persoalan honorer ibarat memperbaiki atap rumah, sementara fondasinya masih retak.
Jika negara sungguh ingin menghadirkan keadilan sosial, maka kebijakan semacam ini harus dibarengi dengan langkah konkret dan terukur untuk menyelesaikan nasib guru dan tenaga kesehatan honorer. Sebab pada akhirnya, keadilan kebijakan bukan soal siapa yang paling baru dibutuhkan, tetapi siapa yang paling lama diabaikan.